Membangun sebuah teologi publik GPIB dalam rangka menghadapi tantangan konteks Indonesia masa kini.
Pdt. Prof. Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D.
Pendahuluan
Kita bertemu untuk membicarakan Tata Gereja. Bagian-bagian pertama dari Tata Gereja memuat Pemahaman Iman, yang disusuli oleh Tata Dasar. Kalau boleh dibandingkan dengan UUD 45, maka Pemahaman Iman itu dapat dibandingkan dengan Mukadimah yang memuat nilai-nilai (yang tidak dapat diubah), sedangkan Tata Dasar merupakan strategi yang kiranya dapat berlaku untuk waktu yang cukup lama, sebelum mengalami perubahan oleh karena tuntutan konteks. Strategi ini sekaligus merupakan perkenalan diri atau self-definition GPIB. Berarti di sini kita berbicara mengenai "Eklesiologi". Namun sebagai gereja Tuhan, maka kita tidak mulai dengan memperkenalkan siapa diri kita. Kita mulai dengan memperkenalkan siapakah Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengerjakan keselamatan bagi dunia ini, dan yang telah mengajak kita untuk ambil bagian dalam Kerajaan Allah yang berkeadilan dan kasih. Tetapi hal ini sudah terkandung di dalam Pemahaman Iman. Maka Pemahaman Iman merupakan "Kristologi". Tata Dasar dimulai dengan perkenalan diri GPIB, disusul dengan visi, misi, dan motto yang bisa dirangkum dalam satu istilah, yaitu "Misi". Untuk dapat menyusun Tata Dasar dengan baik, kita memerlukan pendalaman terhadap tuntutan-tuntutan konteks, dan bagaimana menjawab tuntutan-tuntutan konteks tsb.
Kita bertemu untuk membicarakan Tata Gereja. Bagian-bagian pertama dari Tata Gereja memuat Pemahaman Iman, yang disusuli oleh Tata Dasar. Kalau boleh dibandingkan dengan UUD 45, maka Pemahaman Iman itu dapat dibandingkan dengan Mukadimah yang memuat nilai-nilai (yang tidak dapat diubah), sedangkan Tata Dasar merupakan strategi yang kiranya dapat berlaku untuk waktu yang cukup lama, sebelum mengalami perubahan oleh karena tuntutan konteks. Strategi ini sekaligus merupakan perkenalan diri atau self-definition GPIB. Berarti di sini kita berbicara mengenai "Eklesiologi". Namun sebagai gereja Tuhan, maka kita tidak mulai dengan memperkenalkan siapa diri kita. Kita mulai dengan memperkenalkan siapakah Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengerjakan keselamatan bagi dunia ini, dan yang telah mengajak kita untuk ambil bagian dalam Kerajaan Allah yang berkeadilan dan kasih. Tetapi hal ini sudah terkandung di dalam Pemahaman Iman. Maka Pemahaman Iman merupakan "Kristologi". Tata Dasar dimulai dengan perkenalan diri GPIB, disusul dengan visi, misi, dan motto yang bisa dirangkum dalam satu istilah, yaitu "Misi". Untuk dapat menyusun Tata Dasar dengan baik, kita memerlukan pendalaman terhadap tuntutan-tuntutan konteks, dan bagaimana menjawab tuntutan-tuntutan konteks tsb.
Konteks Indonesia masa kini
Konteks Indonesia masa kini ditandai oleh minimal 5 isyu yang mencolok, yaitu a. Pluralisme budaya dan agama, b. Kemiskinan yang parah, c. Penderitaan dan bencana, d. Ketidakadilan termasuk ketidakadilan gender dan e. Kerusakan ekologi. Kita melihat secara singkat kelima isyu ini.
Konteks Indonesia masa kini ditandai oleh minimal 5 isyu yang mencolok, yaitu a. Pluralisme budaya dan agama, b. Kemiskinan yang parah, c. Penderitaan dan bencana, d. Ketidakadilan termasuk ketidakadilan gender dan e. Kerusakan ekologi. Kita melihat secara singkat kelima isyu ini.
Pluralisme budaya dan agama
Sebenarnya isyu pertama ini tidak asing bagi kita. Dengan menerima prinsip "Bhinneka Tunggal Ika", sebenarnya kepelbagaian budaya telah menjadi sesuatu yang biasa di Indonesia. Namun karena dominasi dari paham nasionalitas atau kebangsaan, orang berbicara mengenai "kebudayaan Indonesia" sebagai sesuatu yang seragam dan monolitis, padahal sudah agak jelas bahwa "menjadi Indonesia" merupakan cita-cita yang sedang kita usahakan bersama-sama. Dalam kenyataan yang ada ialah budaya-budaya lokal Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Maluku, Minahasa dsb. Di masa Orde Baru berwacana kebangsaan, yang mendominasi waktu itu adalah kebudayaan Jawa sebagai model untuk kebudayaan Indonesia. Semua TV swasta menayangkan ketoprak dan wayang, dan tokoh Semar menjadi ikon bagi semua. Sekarang kita belajar bahwa terburu-buru menawarkan sebuah budaya nasional sebagai sebuah barang jadi, dapat menjadi selubung untuk dominasi sebuah budaya lokal tertentu. Maka sikap GPIB terhadap budaya sebaiknya fleksibel saja. Kita menyambut kepelbagaian budaya yang dibawa oleh sekian banyak kelompok etnis di gereja kita, dan kita tidak memutlakkan salah satunya. Kita berpartisipasi di dalam cita-cita "menjadi Indonesia", tetapi kita tidak menolak kalau demi Injil, sebuah bahasa budaya tertentu dipergunakan dalam ibadah (contoh: penggunaan bahasa Mandarin di GPIB Sion Tugu, Jakarta).
Sebenarnya isyu pertama ini tidak asing bagi kita. Dengan menerima prinsip "Bhinneka Tunggal Ika", sebenarnya kepelbagaian budaya telah menjadi sesuatu yang biasa di Indonesia. Namun karena dominasi dari paham nasionalitas atau kebangsaan, orang berbicara mengenai "kebudayaan Indonesia" sebagai sesuatu yang seragam dan monolitis, padahal sudah agak jelas bahwa "menjadi Indonesia" merupakan cita-cita yang sedang kita usahakan bersama-sama. Dalam kenyataan yang ada ialah budaya-budaya lokal Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Maluku, Minahasa dsb. Di masa Orde Baru berwacana kebangsaan, yang mendominasi waktu itu adalah kebudayaan Jawa sebagai model untuk kebudayaan Indonesia. Semua TV swasta menayangkan ketoprak dan wayang, dan tokoh Semar menjadi ikon bagi semua. Sekarang kita belajar bahwa terburu-buru menawarkan sebuah budaya nasional sebagai sebuah barang jadi, dapat menjadi selubung untuk dominasi sebuah budaya lokal tertentu. Maka sikap GPIB terhadap budaya sebaiknya fleksibel saja. Kita menyambut kepelbagaian budaya yang dibawa oleh sekian banyak kelompok etnis di gereja kita, dan kita tidak memutlakkan salah satunya. Kita berpartisipasi di dalam cita-cita "menjadi Indonesia", tetapi kita tidak menolak kalau demi Injil, sebuah bahasa budaya tertentu dipergunakan dalam ibadah (contoh: penggunaan bahasa Mandarin di GPIB Sion Tugu, Jakarta).
Sejak dari zaman Orde Baru kita sudah terbiasa menerima bahwa di Indonesia tidak ada satu agama saja, melainkan 4 agama yang diakui secara resmi, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu dan agama Buddha. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa di luar negeri, Kristen dan Katolik dianggap satu agama saja. Kemudian di zaman pasca Orde Baru kita melihat bahwa agama Konghucu ditambahkan sebagai agama resmi. Bahkan ada perdebatan mengapa pula di Indonesia dibedakan di antara agama "resmi" dan agama "tidak resmi"? Ditambah dengan kenyataan bahwa banyak sekali orang yang menjadi anggota agama resmi, namun kegiatan dan penghayatan keagamaannya mengikuti warisan kepercayaan nenek moyang, yang dulu sering disebut "agama-agama primitif". Di Jawa ada kepercayaan Kebatinan yang sering disebut "agama Jawa", di Sumba ada kepercayaan Marapu dan di Kalimantan Tengah ada kepercayaan Kaharingan. Meskipun kita menerima pembagian resmi di atas, tidak berarti bahwa dalam ranah penghayatan iman Kristen, kita mengapresiasi kepelbagaian agama dan kepercayaan ini. Dulu di zaman misionaris, semua agama lain tidak berharga, orang yang bukan Kristen harus dikristenkan. Sekarang kita tidak sekasar itu lagi, tetapi seringkali peremehan kita terhadap agama lain nampak di dalam ketidaksediaan kita untuk berbicara mengenai tetangga yang beragama lain, dengan merujuk kepadanya sebagai "sesama warganegara Indonesia". Wacana kebangsaan dipakai untuk menutupi kenyataan kepelbagaian agama. Saya sudah membicarakan hal ini panjang lebar, ketika menyinggung kebiasaan gereja-gereja di Indonesia, yang kesemuanya adalah gereja etnis, namun wacananya selalu hanya bersifat kebangsaan saja (Singgih, 2004, 124-157). Kita menuai hasilnya di tahun 1999-2002 di bagian timur Indonesia, yaitu konflik berdarah di Maluku, Halmahera dan Poso. Kalau mau sungguh-sungguh menghargai kepelbagaian ini, maka sikap kita perlu diubah, yaitu menerima keberadaan tetangga kita yang beragama lain daripada kita, meskipun merupakan sesama bangsa Indonesia. Itu berarti hidup dalam dialog, yaitu usaha memahami apa yang bermakna bagi yang lain, tetapi sekaligus usaha menghimbau yang lain agar memahami apa yang bermakna bagi kita.
Kemiskinan yang parah
Media massa sejak zaman Orde Baru mengakui bahwa penduduk miskin Indonesia berjumlah 27.000.000 jiwa, belum termasuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Sesudah diterpa krisis perekonomian yang menyebabkan Indonesia terpuruk dan masih terasa dampaknya sampai sekarang ini, jumlah orang miskin pasti bertambah. Ada yang mengatakan sudah sampai 37.000.000 jiwa, tidak termasuk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kalau semuanya dihitung sebagai kebulatan, barangkali jumlah 50.000.000 jiwa tidak merupakan angka yang mustahil, berarti ¼ dari jumlah penduduk Indonesia adalah miskin, dan menderita karena kemiskinan tsb. Tentunya kita tidak dapat mengatakan bahwa gereja-gereja di Indonesia tidak berbuat apa-apa menghadapi situasi ini. Sejak sidang raya di Surabaya pada akhir tahun 80-an, gereja-gereja menyambut program pemerintah Orde Baru untuk ‘mengentaskan kemiskinan’. Namun dalam waktu singkat wacana di gereja-gereja berubah menjadi ‘mengentaskan kemiskinan di kantong-kantong Kristen (saja)’, dan itupun tidak ketahuan hasilnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa kemiskinan warga gereja di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua berkurang secara signifikan. Juga kemiskinan sering ditutupi dengan pembangunan gedung-gedung peribadatan dan kantor-kantor yang megah, seakan-akan orang Kristen di Indonesia lebih kaya daripada mereka yang beragama lain.
Dalam masa krisis yang multi-dimensional pada tahun-tahun 2000an yl, banyak gereja dan lembaga Kristiani di Yogyakarta mengadakan program "makan siang dari Tuhan" . Jemaat-jemaat mengalokasikan dana untuk keperluan membeli nasi bungkus bagi keperluan makan siang dari para gelandangan, tukang becak dan pekerja-pekerja bangunan misalnya. Namun program makan sekali sehari ini lama kelamaan menjadi sekali seminggu, dan akhirnya berhenti tanpa pengumuman. Padahal krisis belum berakhir malah menjadi semakin berat. Mengapa berhenti? Sekadar sebagai perbandingan saja: USA di tahun 20an pernah mengalami krisis semacam ini. Banyak sekali orang yang jatuh miskin dan bunuh diri. Gereja-gereja menanggapi situasi ini dengan mendirikan dapur umum dan shelter (tempat di mana orang miskin dapat mandi dan menginap semalam dalam keadaan hangat di musim dingin) di kompleks gereja. Sampai sekarang dapur umum dan shelter masih jalan terus dan menjadi bagian permanen dari pelayanan gereja kepada masyarakat. Menurut saya macetnya program di atas di Indonesia disebabkan karena jemaat tidak mengaggap bahwa pelayanan semacam ini merupakan bagian integral dari panggilan gereja. Ada sih diakonia di gereja, tetapi sifatnya insidental, berskala kecil dan hanya ditujukan ke dalam saja. Namun konteks kemiskinan mengharuskan kita untuk tidak lagi menganaktirikan diakonia dibandingkan dengan unsur-unsur tridarma gereja yang lain seperti koinonia (persekutuan) dan marturia (kesaksian).
Media massa sejak zaman Orde Baru mengakui bahwa penduduk miskin Indonesia berjumlah 27.000.000 jiwa, belum termasuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Sesudah diterpa krisis perekonomian yang menyebabkan Indonesia terpuruk dan masih terasa dampaknya sampai sekarang ini, jumlah orang miskin pasti bertambah. Ada yang mengatakan sudah sampai 37.000.000 jiwa, tidak termasuk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kalau semuanya dihitung sebagai kebulatan, barangkali jumlah 50.000.000 jiwa tidak merupakan angka yang mustahil, berarti ¼ dari jumlah penduduk Indonesia adalah miskin, dan menderita karena kemiskinan tsb. Tentunya kita tidak dapat mengatakan bahwa gereja-gereja di Indonesia tidak berbuat apa-apa menghadapi situasi ini. Sejak sidang raya di Surabaya pada akhir tahun 80-an, gereja-gereja menyambut program pemerintah Orde Baru untuk ‘mengentaskan kemiskinan’. Namun dalam waktu singkat wacana di gereja-gereja berubah menjadi ‘mengentaskan kemiskinan di kantong-kantong Kristen (saja)’, dan itupun tidak ketahuan hasilnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa kemiskinan warga gereja di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua berkurang secara signifikan. Juga kemiskinan sering ditutupi dengan pembangunan gedung-gedung peribadatan dan kantor-kantor yang megah, seakan-akan orang Kristen di Indonesia lebih kaya daripada mereka yang beragama lain.
Dalam masa krisis yang multi-dimensional pada tahun-tahun 2000an yl, banyak gereja dan lembaga Kristiani di Yogyakarta mengadakan program "makan siang dari Tuhan" . Jemaat-jemaat mengalokasikan dana untuk keperluan membeli nasi bungkus bagi keperluan makan siang dari para gelandangan, tukang becak dan pekerja-pekerja bangunan misalnya. Namun program makan sekali sehari ini lama kelamaan menjadi sekali seminggu, dan akhirnya berhenti tanpa pengumuman. Padahal krisis belum berakhir malah menjadi semakin berat. Mengapa berhenti? Sekadar sebagai perbandingan saja: USA di tahun 20an pernah mengalami krisis semacam ini. Banyak sekali orang yang jatuh miskin dan bunuh diri. Gereja-gereja menanggapi situasi ini dengan mendirikan dapur umum dan shelter (tempat di mana orang miskin dapat mandi dan menginap semalam dalam keadaan hangat di musim dingin) di kompleks gereja. Sampai sekarang dapur umum dan shelter masih jalan terus dan menjadi bagian permanen dari pelayanan gereja kepada masyarakat. Menurut saya macetnya program di atas di Indonesia disebabkan karena jemaat tidak mengaggap bahwa pelayanan semacam ini merupakan bagian integral dari panggilan gereja. Ada sih diakonia di gereja, tetapi sifatnya insidental, berskala kecil dan hanya ditujukan ke dalam saja. Namun konteks kemiskinan mengharuskan kita untuk tidak lagi menganaktirikan diakonia dibandingkan dengan unsur-unsur tridarma gereja yang lain seperti koinonia (persekutuan) dan marturia (kesaksian).
Penderitaan dan Bencana
Konteks penderitaan dekat dengan konteks kemiskinan. Orang miskin biasanya menderita oleh karena kemiskinannya. Namun bukan hanya orang miskin saja yang menderita melainkan banyak orang lain juga, yang tidak miskin. Dalam dunia modern ini kita melihat penyakit-penyakit lama dan baru yang mengerikan, yang mengakibatkan orang menderita misalnya kanker, HIV-AIDS, ketergantungan pada narkoba. Korban narkoba biasanya sekaligus merupakan korban HIV-AIDS. Keluarga-keluarga mereka sangat menderita juga, bukan saja karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa, melainkan juga dibebani dengan rasa malu yang bukan kepalang menghadapi apa yang terjadi. Akibatnya keluarga memutuskan hubungan dengan si penderita. Penderitaan itu kemudian menjadi penderitaan yang tidak kelihatan oleh karena disembunyikan dari mata umum. Tidak ada gunanya kita mencela sikap ini sebagai sikap yang tidak berperi kemanusiaan. Celaan ini akan semakin mempertebal tembok yang sudah dibangun sebelumnya. Sikap yang benar terhadap konteks penderitaan semacam ini adalah sungguh-sungguh membangun kemampuan pendampingan pastoral dan empati bagi seluruh jajaran pelayanan jemaat (jadi bukan hanya bagi para pendeta saja). Masalahnya tanggapan masyarakat kita (apalagi dari kalangan agamawan) biasanya bukan empati melainkan antipati. Kepada siapa para penderita dapat berharap?
Konteks penderitaan dekat dengan konteks kemiskinan. Orang miskin biasanya menderita oleh karena kemiskinannya. Namun bukan hanya orang miskin saja yang menderita melainkan banyak orang lain juga, yang tidak miskin. Dalam dunia modern ini kita melihat penyakit-penyakit lama dan baru yang mengerikan, yang mengakibatkan orang menderita misalnya kanker, HIV-AIDS, ketergantungan pada narkoba. Korban narkoba biasanya sekaligus merupakan korban HIV-AIDS. Keluarga-keluarga mereka sangat menderita juga, bukan saja karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa, melainkan juga dibebani dengan rasa malu yang bukan kepalang menghadapi apa yang terjadi. Akibatnya keluarga memutuskan hubungan dengan si penderita. Penderitaan itu kemudian menjadi penderitaan yang tidak kelihatan oleh karena disembunyikan dari mata umum. Tidak ada gunanya kita mencela sikap ini sebagai sikap yang tidak berperi kemanusiaan. Celaan ini akan semakin mempertebal tembok yang sudah dibangun sebelumnya. Sikap yang benar terhadap konteks penderitaan semacam ini adalah sungguh-sungguh membangun kemampuan pendampingan pastoral dan empati bagi seluruh jajaran pelayanan jemaat (jadi bukan hanya bagi para pendeta saja). Masalahnya tanggapan masyarakat kita (apalagi dari kalangan agamawan) biasanya bukan empati melainkan antipati. Kepada siapa para penderita dapat berharap?
Kita juga menemukan orang yang menderita karena mengalami kekerasan. Hampir setia[p hari kita menyaksikan kekerasan terjadi di berbagai bidang, termasuk rumah tangga. Kita membaca mengenai anak-anak jalanan yang setiap kali kena penggarukan, dan mengalami berbagai perlakuan kejam dari para petugas. Orang-orang yang ditahan polisi dan belum diadili, tetapi sudah babak belur dihajar sampai setengah mati, dan tidak jarang ada yang mati dalam tahanan. Orang-orang yang dituduh atau tertangkap basah mencuri, menjadi sasaran amuk massa, yang tidak segan-segan menyiksa dan membunuh dengan cara kejam. Konflik-konflik antar kelompok, antar desa, antar golongan bahkan antar etnis terjadi karena sumber-sumber kehidupan semakin menjadi langka, dan dalam rangka itu HAM diabaikan saja oleh karena kepentingan kelompok dianggap paling penting. Sebagai gereja anggota PGI kita menerima konsep dasawarsa non-kekerasan dari Dewan Gereja Sedunia, tetapi kita tidak punya idea sama sekali bagaimana hidup berdampingan satu sama lain tanpa kekerasan dapat diwujudkan di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Menghadapi kekerasan, kita semua habis akal.
Meskipun sebelumnya sudah terjadi berbagai bencana alam di Indonesia, tsunami Aceh dan gempa bumi Nias dapat dianggap sebagai mulainya masa bencana alam di Indonesia, yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan bangsa, dan sebagai akibatnya , jumlah orang yang menderita dan menjadi miskin semakin bertambah pula. Setelah gempa bumi di Yogyakarta 2006 kita menemukan ratusan orang yang harus hidup sebagai penyandang cacat atau lumpuh total dan hanya tergeletak di tempat tidur. Meskipun mendapat bantuan dari pelbagai pihak untuk pembangunan kembali rumah-rumah yang telah roboh atau hancur, suasana tidak kembali seperti semula. Ada cukup banyak orang dan keluarga, yang setelah mengalami gempa bumi, kembali menjadi korban angin puting beliung. Beberapa gereja memberi tanggapan yang memadai terhadap bencana ini, misalnya GKI yang menolong korban gempa bumi di Aceh dan Nias, dan gereja-gereja Mennonite yang membantu korban gempa di daerah Pundung, Bantul yang rata dengan tanah. Karya mereka demikian mengesankan, sehingga lasykar Hisbullah (anak buah Kyai Abu Bakar Baasyir) tidak segan-segan untuk ikut berpartisipasi di dalam karya ini, mula-mula dengan 33 orang tetapi kemudian menyusul dengan 100 sukarelawan. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, tanggapan gereja-gereja di Indonesia terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia belum memadai. Mungkin kita masih terbius dengan teologi tertentu, yang menganggap bencana alam sebagai wujud hukuman Tuhan terhadap orang berdosa.
Meskipun sebelumnya sudah terjadi berbagai bencana alam di Indonesia, tsunami Aceh dan gempa bumi Nias dapat dianggap sebagai mulainya masa bencana alam di Indonesia, yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan bangsa, dan sebagai akibatnya , jumlah orang yang menderita dan menjadi miskin semakin bertambah pula. Setelah gempa bumi di Yogyakarta 2006 kita menemukan ratusan orang yang harus hidup sebagai penyandang cacat atau lumpuh total dan hanya tergeletak di tempat tidur. Meskipun mendapat bantuan dari pelbagai pihak untuk pembangunan kembali rumah-rumah yang telah roboh atau hancur, suasana tidak kembali seperti semula. Ada cukup banyak orang dan keluarga, yang setelah mengalami gempa bumi, kembali menjadi korban angin puting beliung. Beberapa gereja memberi tanggapan yang memadai terhadap bencana ini, misalnya GKI yang menolong korban gempa bumi di Aceh dan Nias, dan gereja-gereja Mennonite yang membantu korban gempa di daerah Pundung, Bantul yang rata dengan tanah. Karya mereka demikian mengesankan, sehingga lasykar Hisbullah (anak buah Kyai Abu Bakar Baasyir) tidak segan-segan untuk ikut berpartisipasi di dalam karya ini, mula-mula dengan 33 orang tetapi kemudian menyusul dengan 100 sukarelawan. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, tanggapan gereja-gereja di Indonesia terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia belum memadai. Mungkin kita masih terbius dengan teologi tertentu, yang menganggap bencana alam sebagai wujud hukuman Tuhan terhadap orang berdosa.
Ketidakadilan termasuk ketidakadilan gender
Konteks inipun masih dapat dikaitkan dengan kedua konteks sebelumnya, namun secara khusus di sini saya berbicara mengenai mereka yang tidak miskin, namun mengalami diskriminasi dalam masyarakat, baik yang secara terang-terangan maupun secara diam-diam (ataupun diimajinasikan). Pada zaman Orde Baru orang selalu membantah bahwa ada perlakuan diskriminatif terhadap saudara/i keturunan Tionghoa. Tetapi pada era Reformasi muncul pengakuan bahwa sikap diskriminatif ini negatif dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan terutama mantan presiden Abdurrahman Wahid patut dihargai sebagai mengakhiri diskriminasi tsb. Namun tetap saja kita mendengar laporan bahwa orang-orang keturunan Tionghoa mendapat kesulitan kalau mau masuk ke perguruan tinggi, oleh karena harus menyediakan surat-surat yang menandakan bahwa mereka adalah "WNI", padahal yang lain tidak perlu memenuhi persyaratan tsb. Sama halnya kalau mereka memerlukan paspor. Birokrasi Indonesia masih diskriminatif! Kemudian kita melihat gejala diskriminasi ini juga terhadap kalangan Kristiani, yang harus mengurus surat izin 2 menteri apabila ingin mendirikan rumah ibadah, dan terutama izin dari masyarakat sekitar, itulah yang menjadi halangan terbesar, karena hampir pasti tidak akan diberikan. Perjuangan kita terhadap kedua diskriminasi ini tentunya harus dilakukan, terutama di bidang politik, tetapi berbeda dengan beberapa teman yang menganggap bahwa diskriminasi kedua inilah pokok yang paling penting karena melanggar hak dan kebebasan beragama yang sudah dijamin oleh piagam HAM, saya menekankan bahwa gereja-gereja seharusnya tidak hanya memperjuangkan satu pokok HAM saja, tetapi semua pokok di dalam piagam HAM tsb. Dengan demikian baru jelas bahwa kita tidak hanya memperjuangkan kepentingan diri kita sendiri saja, tetapi juga kepentingan bersama yang nampak pada penderitaan orang lain.
Konteks inipun masih dapat dikaitkan dengan kedua konteks sebelumnya, namun secara khusus di sini saya berbicara mengenai mereka yang tidak miskin, namun mengalami diskriminasi dalam masyarakat, baik yang secara terang-terangan maupun secara diam-diam (ataupun diimajinasikan). Pada zaman Orde Baru orang selalu membantah bahwa ada perlakuan diskriminatif terhadap saudara/i keturunan Tionghoa. Tetapi pada era Reformasi muncul pengakuan bahwa sikap diskriminatif ini negatif dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan terutama mantan presiden Abdurrahman Wahid patut dihargai sebagai mengakhiri diskriminasi tsb. Namun tetap saja kita mendengar laporan bahwa orang-orang keturunan Tionghoa mendapat kesulitan kalau mau masuk ke perguruan tinggi, oleh karena harus menyediakan surat-surat yang menandakan bahwa mereka adalah "WNI", padahal yang lain tidak perlu memenuhi persyaratan tsb. Sama halnya kalau mereka memerlukan paspor. Birokrasi Indonesia masih diskriminatif! Kemudian kita melihat gejala diskriminasi ini juga terhadap kalangan Kristiani, yang harus mengurus surat izin 2 menteri apabila ingin mendirikan rumah ibadah, dan terutama izin dari masyarakat sekitar, itulah yang menjadi halangan terbesar, karena hampir pasti tidak akan diberikan. Perjuangan kita terhadap kedua diskriminasi ini tentunya harus dilakukan, terutama di bidang politik, tetapi berbeda dengan beberapa teman yang menganggap bahwa diskriminasi kedua inilah pokok yang paling penting karena melanggar hak dan kebebasan beragama yang sudah dijamin oleh piagam HAM, saya menekankan bahwa gereja-gereja seharusnya tidak hanya memperjuangkan satu pokok HAM saja, tetapi semua pokok di dalam piagam HAM tsb. Dengan demikian baru jelas bahwa kita tidak hanya memperjuangkan kepentingan diri kita sendiri saja, tetapi juga kepentingan bersama yang nampak pada penderitaan orang lain.
Peranan perempuan cukup jelas baik dialam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Dalam era Reformasi kita melihat bagaimana masalah pembagian kerja secara seksual, ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan menjadi sorotan utama. Jadi bukan sekadar peranan perempuan lagi yang dipermasalahkan, sebab sekarangpun peranan presiden sudah bisa dijalankan oleh perempuan (Ibu Megawati). Kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, semua media massa menyorotinya beramai-ramai. Pemukulan terhadap istri dan/atau anak, demikian juga PRT atau TKW sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat, dan siapa yang melakukan kekerasan tsb akan berhadapan dengan pengadilan. Meskipun demikian tidak berarti permasalahan perempuan sudah selesai. Hal ini disebabkan oleh karena seringkali perempuan yang telah berada dalam peranan yang menentukan ini, dalam kenyataan lebih banyak mengurusi kepentingan laki-laki daripada kepentingan perempuan. Kita juga dikagetkan oleh laporan internasional bahwa Indonesia merupakan negara yang pemerintahnya paling lalai dalam mengatasi masalah perdagangan perempuan dan anak-anak, padahal hal inilah yang menjadi bisnis gelap dan punya mata rantai di mana-mana. Apakah GPIB siap untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk dapat mengabdi sepenuhnya di gereja dan di masyarakat, apalagi kalau jumlah pendeta dan calon pendeta dari pihak perempuan sudah lebih banyak dari laki-laki?
Kerusakan ekologis
Isyu ini sangat mencuat, terutama dalam tayangan-tayangan TV mengenai kerusakan hebat dari hutan-hutan Indonesia akibat penebangan-penebangan illegal, yang sepertinya berjalan terus tanpa dapat dihentikan, juga oleh pemerintah. Akibat penggundulan hutan, iklim berubah, dan karena iklim berubah, pertanian mengalami kemunduran. Kita mengalami kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang dahsyat sehingga menyebabkan banjir bandang akibat pohon-pohon yang menahan air sudah tidak ada, dan kita mengalami efek rumah kaca: tempat-tempat yang dulunya sejuk seperti Salatiga menjadi panas. Kerusakan ekologis ini juga mengakibatkan bencana-bencana seperti tanah longsor dan gelombang besar, yang pada gilirannya menimbulkan pasang air laut, yang bahkan bisa terjadi di ibukota Jakarta (Muara Karang). Kita menuai kesalahan besar yang telah dibuat oleh penggagas-penggagas industrialisasi di masa lalu, yang memperkembangkan teknologi tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Meskipun semua fabrik mempersiapkan laporan AMDAL, kesan masyarakat adalah bahwa laporan tsb dilakukan sebagai formalitas saja. Di Yogyakarta berdirilah mal-mal raksasa. Dampaknya ialah pengurangan air bagi warga sekitar, karena semua tersedot untuk keperluan mal-mal tsb. Tetapi apa yang dapat dilakukan? Pembangunan mal-mal tsb mendapat dukungan dari semua pihak. Tidak ada yang mempedulikan keluhan warga-warga sekitar, yang sekarang harus membeli air, padahal tadinya tidak perlu. Apakah GPIB siap untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat dan wajar bagi semua? Di dalam Pemahaman Iman GPIB isyu ini sudah dimasukkan, tetapi sejauh ini belum ada diskusi yang memadai mengenai masalah-masalah kerusakan ekologis di sekitar kita.
Isyu ini sangat mencuat, terutama dalam tayangan-tayangan TV mengenai kerusakan hebat dari hutan-hutan Indonesia akibat penebangan-penebangan illegal, yang sepertinya berjalan terus tanpa dapat dihentikan, juga oleh pemerintah. Akibat penggundulan hutan, iklim berubah, dan karena iklim berubah, pertanian mengalami kemunduran. Kita mengalami kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang dahsyat sehingga menyebabkan banjir bandang akibat pohon-pohon yang menahan air sudah tidak ada, dan kita mengalami efek rumah kaca: tempat-tempat yang dulunya sejuk seperti Salatiga menjadi panas. Kerusakan ekologis ini juga mengakibatkan bencana-bencana seperti tanah longsor dan gelombang besar, yang pada gilirannya menimbulkan pasang air laut, yang bahkan bisa terjadi di ibukota Jakarta (Muara Karang). Kita menuai kesalahan besar yang telah dibuat oleh penggagas-penggagas industrialisasi di masa lalu, yang memperkembangkan teknologi tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Meskipun semua fabrik mempersiapkan laporan AMDAL, kesan masyarakat adalah bahwa laporan tsb dilakukan sebagai formalitas saja. Di Yogyakarta berdirilah mal-mal raksasa. Dampaknya ialah pengurangan air bagi warga sekitar, karena semua tersedot untuk keperluan mal-mal tsb. Tetapi apa yang dapat dilakukan? Pembangunan mal-mal tsb mendapat dukungan dari semua pihak. Tidak ada yang mempedulikan keluhan warga-warga sekitar, yang sekarang harus membeli air, padahal tadinya tidak perlu. Apakah GPIB siap untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat dan wajar bagi semua? Di dalam Pemahaman Iman GPIB isyu ini sudah dimasukkan, tetapi sejauh ini belum ada diskusi yang memadai mengenai masalah-masalah kerusakan ekologis di sekitar kita.
Demikianlah secara singkat uraian mengenai kelima konteks di mana kita berada. Tanggapan terhadap Pembicaraan mengenai teologi publik GPIB mau tidak mau haruslah menyentuh kelima isyu ini secara memadai.
Refleksi mengenai identitas kita
Sesudah menguraikan konteks, langkah berikut adalah membayangkan usaha berteologi yang memadai dalam rangka menanggapi konteks tsb. Namun sebelum itu kita perlu berefleksi kembali mengenai identitas kita sebagai GPIB dan keberadaan kita sebagai bagian dari Indonesia. Masalah identitas memang merupakan sesuatu yang ramai dibicarakan. Tentu kita tidak dapat membahasnya sampai tuntas, namun baiklah di sini saya membatasi bahwa di satu pihak kita membutuhkan identitas. Maka secara pribadi maupun organisatoris, kita perlu membangun kepribadian yang kuat. Namun pada saat yang sama, identitas itu bukanlah sesuatu yang statis dan selesai, kuat bagaimanapun dia itu. Identitas yang sehat adalah identitas yang sehat namun terbuka. Berdasarkan keterbukaan inilah kita dapat melihat kembali pada a/GPIB itu apa? Dan b/Indonesia itu apa? Mau tidak mau refleksi ini bersifat auto-kritik, oleh karena yang mau dicapai adalah perubahan sikap secara menyeluruh.
a/GPIB itu apa?
Sesudah menguraikan konteks, langkah berikut adalah membayangkan usaha berteologi yang memadai dalam rangka menanggapi konteks tsb. Namun sebelum itu kita perlu berefleksi kembali mengenai identitas kita sebagai GPIB dan keberadaan kita sebagai bagian dari Indonesia. Masalah identitas memang merupakan sesuatu yang ramai dibicarakan. Tentu kita tidak dapat membahasnya sampai tuntas, namun baiklah di sini saya membatasi bahwa di satu pihak kita membutuhkan identitas. Maka secara pribadi maupun organisatoris, kita perlu membangun kepribadian yang kuat. Namun pada saat yang sama, identitas itu bukanlah sesuatu yang statis dan selesai, kuat bagaimanapun dia itu. Identitas yang sehat adalah identitas yang sehat namun terbuka. Berdasarkan keterbukaan inilah kita dapat melihat kembali pada a/GPIB itu apa? Dan b/Indonesia itu apa? Mau tidak mau refleksi ini bersifat auto-kritik, oleh karena yang mau dicapai adalah perubahan sikap secara menyeluruh.
a/GPIB itu apa?
Secara normatif dapat dilihat di Tata Gereja. Tetapi secara sosiologis GPIB adalah gereja diaspora beberapa kelompok etnis dari sebelah timur Indonesia (Maluku, Minahasa dan Timor, kemudian bertambah dengan kelompok etnis lain). Dengan keberadaannya yang terdiri dari tiga kelompok etnis yang besar, kemudian beberapa kelompok etnis lain, maka GPIB bukan sebuah "gereja etnis" yang warganya hanya terdiri dari satu kelompok etnis saja. Saya menggunakan istilah "gereja diaspora-etnis" untuk GPIB, untuk membedakannya dari gereja-gereja etnis seperti HKBP dan GKJ. Tentu saja, idealnya, kepelbagaian etnis di GPIB ini dapat kita jadikan landasan untuk berpartisipasi di dalam cita-cita "menjadi Indonesia" di dalam wujud "gereja Indonesia". Namun perasaan saya, etnisitas masih mendominasi pemikiran di GPIB. Kemudian ada warisan-warisan GPIB dari masa lalu, yaitu konsep pemikiran mengenai gereja-negara (Indische Kerk), warisan Calvinisme dan Pietisme. Di negara-negara Barat, gereja-negara biasanya sekaligus dianggap "gereja nasional" seperti misalnya Church of Scotland. Meskipun sudah lama GPIB tidak lagi merupakan gereja-negara, sisa-sisa dari masa lalu ini masih nampak dalam kecenderungan untuk menganggap GPIB adalah "gereja nasional" (padahal bukan) dan dekat dengan pemerintah atau para pejabat negara. Juga pengaruh ini nampak pada tekanan mengenai para presbiter GPIB sebagai "pejabat". Hal ini tentu dipengaruhi juga oleh Calvinisme, yang menekankan pada mereka yang dipanggil menjadi dignitaris. Artinya "pejabat".
Di dalam konteks Indonesia, istilah "pejabat" itu dimaknai sebagai pejabat dalam pengertian atasan atau penguasa, jadi amat bertolakbelakang dari makna hamba atau pelayan Tuhan. Kepejabatan berhubungan langsung dengan birokrasi. Maka sebuah masalah besar di GPIB adalah birokratisisme, yang kadang-kadang lebih kaku daripada yang seharusnya.Warisan Pietisme adalah sikap yang a-politis, dalam arti tidak mau berurusan dengan masalah-masalah atau isyu-isyu penting yang sedang berlaku didalam konteks. Warisan Pietisme ini kadang-kadang dapat berfungsi sebagai alternatif terhadap birokratisisme, namun secara keseluruhan kesemua warisan ini hanya membuat GPIB mengarah ke dalam, introvert dan mengurusi urusan-urusan ritual-domestik saja, misinya cuma bagaimana menambah jumlah anggota, dan tidak ada keterarahan institusional terhadap dunia yang harus dilayaninya. Disini saya memperlihatkan bahwa warisan-warisan teologis yang kita terima dari pendahulu-pendahulu kita tidak membantu kita dalam usaha membangun sebuah teologi publik, tetapi jangan putus asa dulu oleh karena itu baru sebagian dari warisan-warisan kita, sebagian yang lain dapat dipergunakan secara kreatif dan positif, dan hal itu akan saya sebutkan di bagian muatan teologi publik.
b/Indonesia itu apa?
Secara normatif dapat dilihat dalam pelbagai terbitan formal, namun dalam wacana publik, keindonesiaan dibicarakan dalam kerangka civil society. Istilah "civil society" tidak dapat diartikan sebagai "masyarakat sipil" sebagai antitesa dari "masyarakat militer", meskipun jelas bahwa di dalam civil society kita menentang pengaruh militerisme (yang tidak identik dengan "militer" dan karena itu membangun civil sociery tidak berarti anti pada kalangan militer). Civil society berhubungan dengan istilah "civilized" dan "civilization", suatu masyarakat beradab yang didasarkan atas keadilan, kebebasan dan toleransi. Dalam diskusi mengenai civil society di Indonesia, apalagi kalau dikaitkan dengan istilah "masyarakat madani", maka dasarnya bukan keadilan, kebebasan dan toleransi, melainkan hukum. Bukannya hukum tidak penting. Masyarakat kita sakit karena hukum dilecehkan. Segala cara dapat dilakukan untuk memelintir hukum sehingga memenuhi kepentingan sendiri. Namun civil society yang berdasarkan hukum saja tidak cukup. Sebuah negara hukumpun bisa melanggar HAM dan bersifat diskriminatif. Maka civil society tetap harus berdasarkan ketiga hal di atas.
Secara normatif dapat dilihat dalam pelbagai terbitan formal, namun dalam wacana publik, keindonesiaan dibicarakan dalam kerangka civil society. Istilah "civil society" tidak dapat diartikan sebagai "masyarakat sipil" sebagai antitesa dari "masyarakat militer", meskipun jelas bahwa di dalam civil society kita menentang pengaruh militerisme (yang tidak identik dengan "militer" dan karena itu membangun civil sociery tidak berarti anti pada kalangan militer). Civil society berhubungan dengan istilah "civilized" dan "civilization", suatu masyarakat beradab yang didasarkan atas keadilan, kebebasan dan toleransi. Dalam diskusi mengenai civil society di Indonesia, apalagi kalau dikaitkan dengan istilah "masyarakat madani", maka dasarnya bukan keadilan, kebebasan dan toleransi, melainkan hukum. Bukannya hukum tidak penting. Masyarakat kita sakit karena hukum dilecehkan. Segala cara dapat dilakukan untuk memelintir hukum sehingga memenuhi kepentingan sendiri. Namun civil society yang berdasarkan hukum saja tidak cukup. Sebuah negara hukumpun bisa melanggar HAM dan bersifat diskriminatif. Maka civil society tetap harus berdasarkan ketiga hal di atas.
Ranah publik dipengaruhi oleh 3 poros kekuasaan: negara, pasar dan komunitas. Negara berkaitan dengan politik, pasar berkaitan dengan ekonomi dan komunitas berkaitan dengan agama/budaya. Ketiga-tiganya seharusnya berada dalam keadaan yang sama kuat alias berimbang bagaikan segitiga samasisi. Ketiganya di satu pihak berdiri sendiri tetapi tidak independent, melainkan interdependent. Yang satu tidak bisa tanpa yang lain, tetapi bukan berarti satu tunduk kepada yang lain. Di masa Orde Baru yang paling kuat adalah sisi Negara/Pemerintah, sedemikian rupa sehingga kedua sisi yang lain berada di bawah dominasinya. Dengan sendirinya banyak persoalan yang berat muncul dan sampai sekarang terasa akibatnya: ekonomi yang carut marut, komunitas yang kehilangan sensibilitas sosialnya dan mudah mengambil langkah-langkah kekerasan (trial by the crowd). Maka yang dapat dilakukan di dalam pembangunan masyarakat beradab adalah mengembalikan keseimbangan pada ketiga sisi, sehingga dengan demikian kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan wajar. Kalau pada masa Orde Baru terjadi dominasi Negara/pemerintah, maka pada masa kini, kita jangan mengembalikan lagi dominasi tsb, seperti kadang-kadang kita dengar di media massa. Bahkan negara sendiri sudah terbagi atas tiga kekuasaan: eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan ketiga-tiganya sedang belajar untuk tidak memaksakan kehendak terhadap satu dengan yang lain.
Pasar (Ekonomi, Globalisasi)
Ranah
Publik
Negara (Politik, Demokrasi/desentralisasi)
Komunitas
(Agama/Budaya, Kontekstualisasi)
Ranah
Publik
Negara (Politik, Demokrasi/desentralisasi)
Komunitas
(Agama/Budaya, Kontekstualisasi)
Kalau kita menghubungkan segitiga samasisi ini dengan kehidupan gereja-gereja di Indonesia, maka secara kasar kita dapat mengatakan bahwa GKI secara tradisional berada di sisi Pasar, GKJ dan HKBP secara tradisional berada di sisi Komunitas dan GPIB secara tradisional berada di sisi Negara (karena warisan staatskerk-nya itu). Panggilan gereja cukup sulit oleh karena di satu pihak dia mestinya bersolider dengan sisinya itu, di pihak lain, sebagai gereja Tuhan, dia tidak boleh mengidentifikasikan diri secara total pada salah satu dari ketiga sisi tsb! Maka pergumulan GKI, GKJ, HKBP dan GPIB adalah pergumulan ganda: solider dengan sisinya, namun berani menjaga distansi dengan sisinya itu, dengan jalan menjalankan tugas kenabian: kritik yang bersifat membangun terhadap kekurangan-kekurangan setiap sisi. Jadi GPIB seharusnya merupakan bagian dari civil society yang sedang dibangun (dengan susah payah!), yang memperjuangkan agar keseimbangan poros-poros kekuasaan di atas terpelihara dengan baik. Itulah secara horisontal teologi publik GPIB.
Muatan teologi publik
Akhirnya kita dapat berbicara mengenai teologi publik. Ungkapan teologi publik berasal dari dunia Barat dan menunjuk pada tanggapan gereja terhadap isyu-isyu politis yang mencuat di masyarakat. Tentu saja banyak orang di luar sana yang telah membicarakan teologi publik. Saya mengacu pada Duncan Forrester dari Edinburgh, Scotland yang teorinya sudah dimodifikasi untuk keperluan Indonesia oleh kolega saya Yahya Wijaya (Wijaya, 2005). Forrester memperlihatkan 5 sikap terhadap politik, yaitu teologi pietistik, komunitarianisme, chaplaincy, pembebasan dan teologi publik. Menurut Yahya di Indonesia hanya ada 3 sikap yang menonjol, yaitu sikap teologi pietistik, teologi chaplaincy dan teologi pembebasan.
Pietisme kurang peduli pada teologi politik oleh karena menekankan pada keselamatan jiwa dan kesucian hidup pribadi. Sikapnya adalah a-politis. Karena itu maka para pekabar injil di zaman kolonial dapat berhubungan baik dengan penguasa-penguasa kolonial, sehingga memungkinkan pengiriman para misionaris, yang menabur benih berdirinya gereja-gereja di Indonesia. Karena latar belakang yang seperti ini maka tidak mengherankan apabila warna pietisme amat menonjol. Banyak teolog Indonesia, yang karena berusaha membangun pendekatan-pendekatan teologis yang berwawasan sosial, dicap sebagai "liberal" oleh sebagian warga jemaat. Sikap a-politis dari kalangan pietis (sekarang ditambah dengan kalangan kharismatis) berubah pada masa kini, tetapi cenderung terfokus pada hak-hak politik komunitas Kristen, seperti hak untuk membangun gedung gereja dan hak untuk mewartakan Injil. Kata Yahya, tentang isyu-isyu politik yang lebih luas, mereka cenderung tidak peduli atau bersikap oportunistik. Teologi chaplaincy muncul ketika agama Kristen telah menyebar luas menjadi agama mayoritas dalam masyarakat Barat. Maka pemerintahan yang ada ialah pemerintahan Kristiani, Christendom. Menurut Forrester, Christendom menandai masuknya kekeristenan ke dalam ranah public. Pada era inilah gereja mulai melakukan pendekatan chaplaincy, yaitu memandang para pemegang kekuasaan sebagai sasaran layanan pastoral. Pendekatan ini berusaha mencari bimbingan Injil bagi penguasa dan mengatur sistem politik dan ekonomi menurut kriteria yang sesuai dengan iman Kristen. Meskipun umat Kristiani di Indonesia bukan mayoritas, sikap teologis ini nampak dalam jemaat, misalnya dalam doa-doa syafaat yang berkaitan dengan doa untuk pejabat pemerintah, agar selalu berada di bawah perlindungan dan berkat ilahi. Di lain pihak, teologi pembebasan muncul sebagai kritik terhadap teologi chaplaincy yang dianggap sebagai menerima status quo yang ada, padahal status quo tsb bersifat tidak adil dan menindas.
Teologi chaplaincy dalam konteks negara-negara dunia ketiga di mana agama Kristen merupakan minoritas, sering berjalan bersama Teologi Pembangunan, yang mendukung program pembangunan pemerintah. Tetapi program pembangunan ini dikritik sebagai developmentalism yang hanya menguntungkan kelas masyarakat menengah ke atas dan pemilik modal besar, sementara hidup kaum miskin dikorbankan. Di samping itu di Indonesia, teologi chaplaincy berjalan bersama dengan semacam Teologi Kebangsaan, di mana wacana kebangsaan menjadi kendaraan bagi pemikiran-pemikiran teologis Kristen. Dalam menanggapi wacana mengenai ranah publik di atas, maka kita perlu berpindah dari teologi chaplaincy ke teologi public. Di satu pihak teologi publik lebih memungkinakan sikap kritis, tetapi di pihak lain dia tidak perlu mengambil posisi anti struktur seperti diperlihatkan oleh teologi pembebasan. Muatan teologi publik secara vertikal adalah sbb: a. Theo-logy /Spirituality (what kind of God?), b.Ecclesiology (what kind of church-community?), c.Missiology (what kind of action?)
Akhirnya kita dapat berbicara mengenai teologi publik. Ungkapan teologi publik berasal dari dunia Barat dan menunjuk pada tanggapan gereja terhadap isyu-isyu politis yang mencuat di masyarakat. Tentu saja banyak orang di luar sana yang telah membicarakan teologi publik. Saya mengacu pada Duncan Forrester dari Edinburgh, Scotland yang teorinya sudah dimodifikasi untuk keperluan Indonesia oleh kolega saya Yahya Wijaya (Wijaya, 2005). Forrester memperlihatkan 5 sikap terhadap politik, yaitu teologi pietistik, komunitarianisme, chaplaincy, pembebasan dan teologi publik. Menurut Yahya di Indonesia hanya ada 3 sikap yang menonjol, yaitu sikap teologi pietistik, teologi chaplaincy dan teologi pembebasan.
Pietisme kurang peduli pada teologi politik oleh karena menekankan pada keselamatan jiwa dan kesucian hidup pribadi. Sikapnya adalah a-politis. Karena itu maka para pekabar injil di zaman kolonial dapat berhubungan baik dengan penguasa-penguasa kolonial, sehingga memungkinkan pengiriman para misionaris, yang menabur benih berdirinya gereja-gereja di Indonesia. Karena latar belakang yang seperti ini maka tidak mengherankan apabila warna pietisme amat menonjol. Banyak teolog Indonesia, yang karena berusaha membangun pendekatan-pendekatan teologis yang berwawasan sosial, dicap sebagai "liberal" oleh sebagian warga jemaat. Sikap a-politis dari kalangan pietis (sekarang ditambah dengan kalangan kharismatis) berubah pada masa kini, tetapi cenderung terfokus pada hak-hak politik komunitas Kristen, seperti hak untuk membangun gedung gereja dan hak untuk mewartakan Injil. Kata Yahya, tentang isyu-isyu politik yang lebih luas, mereka cenderung tidak peduli atau bersikap oportunistik. Teologi chaplaincy muncul ketika agama Kristen telah menyebar luas menjadi agama mayoritas dalam masyarakat Barat. Maka pemerintahan yang ada ialah pemerintahan Kristiani, Christendom. Menurut Forrester, Christendom menandai masuknya kekeristenan ke dalam ranah public. Pada era inilah gereja mulai melakukan pendekatan chaplaincy, yaitu memandang para pemegang kekuasaan sebagai sasaran layanan pastoral. Pendekatan ini berusaha mencari bimbingan Injil bagi penguasa dan mengatur sistem politik dan ekonomi menurut kriteria yang sesuai dengan iman Kristen. Meskipun umat Kristiani di Indonesia bukan mayoritas, sikap teologis ini nampak dalam jemaat, misalnya dalam doa-doa syafaat yang berkaitan dengan doa untuk pejabat pemerintah, agar selalu berada di bawah perlindungan dan berkat ilahi. Di lain pihak, teologi pembebasan muncul sebagai kritik terhadap teologi chaplaincy yang dianggap sebagai menerima status quo yang ada, padahal status quo tsb bersifat tidak adil dan menindas.
Teologi chaplaincy dalam konteks negara-negara dunia ketiga di mana agama Kristen merupakan minoritas, sering berjalan bersama Teologi Pembangunan, yang mendukung program pembangunan pemerintah. Tetapi program pembangunan ini dikritik sebagai developmentalism yang hanya menguntungkan kelas masyarakat menengah ke atas dan pemilik modal besar, sementara hidup kaum miskin dikorbankan. Di samping itu di Indonesia, teologi chaplaincy berjalan bersama dengan semacam Teologi Kebangsaan, di mana wacana kebangsaan menjadi kendaraan bagi pemikiran-pemikiran teologis Kristen. Dalam menanggapi wacana mengenai ranah publik di atas, maka kita perlu berpindah dari teologi chaplaincy ke teologi public. Di satu pihak teologi publik lebih memungkinakan sikap kritis, tetapi di pihak lain dia tidak perlu mengambil posisi anti struktur seperti diperlihatkan oleh teologi pembebasan. Muatan teologi publik secara vertikal adalah sbb: a. Theo-logy /Spirituality (what kind of God?), b.Ecclesiology (what kind of church-community?), c.Missiology (what kind of action?)
a. Theo-logy /Spirituality
Saya menaruh tanda sambung di antara "theo" dan "logy", untuk menunjukkan bahwa teologi di sini bukan merujuk pada pembicaraan umum mengenai teologi, tetapi pemahaman kita terhadap siapakah Tuhan dan Tuhan yang bagaimanakah yang menurut kita dapat menjawab tantangan-tantangan konteks Indonesia masa kini. Bukan Tuhan yang kita utik-utik, melainkan gambaran atau idea mengenai Tuhan yang relevan dan kontekstual. Dalam rangka memeriksa gambaran Tuhan ini kita tidak perlu meninggalkan warisan-warisan teologis yang telah kita terima dari pendahulu-pendahulu kita. Isi kelima isyu dalam konteks tadi membutuhkan Tuhan yang peduli di dalam kasihNya yang besar terhadap dunia ini. Maka teks Yohanes 3:16 menurut saya masih amat relevan. Oleh karena kasihNya yang habis-habisan terhadap dunia yang diciptakanNya, Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk melaksanakan karya penyelamatan. Karya penyelamatan ini tidak usah dimaknai secara abstrak atau sepotong-sepotong, melainkan menyeluruh, supaya manusia mengalami "hidup yang berkelimpahan" (Yoh 10:10). Dalam diskusi kita ada saran bahwa kita jangan terlalu mencolok menggambarkan Tuhan dalam wujud Trinitas atau Ketritunggalan, berhubung kita berada dalam konteks di mana Islam adalah mayoritas, dan seperti diketahui secara normatif Islam menolak paham Ketritunggalan ilahi. Namun menurut saya dialog dengan Islam tidak menuntut agar kita mengurangi pokok kepercayaan kita. Dialog berarti saya berusaha memahami yang lain, dan himbauan agar yang lain memahami saya. Bagaimana yang lain bisa memahami saya kalau apa yang menjadi pokok kepercayaan saya dihilangkan atau disembunyikan? Tentu saja kita perlu menghayati Ketritunggalan secara kontekstual, dan itu berarti menafsirkannya secara non-triumfalistik sebagai wujud solidaritas ilahi kepada manusia, seperti yang telah saya cobakan di atas.
Saya menaruh tanda sambung di antara "theo" dan "logy", untuk menunjukkan bahwa teologi di sini bukan merujuk pada pembicaraan umum mengenai teologi, tetapi pemahaman kita terhadap siapakah Tuhan dan Tuhan yang bagaimanakah yang menurut kita dapat menjawab tantangan-tantangan konteks Indonesia masa kini. Bukan Tuhan yang kita utik-utik, melainkan gambaran atau idea mengenai Tuhan yang relevan dan kontekstual. Dalam rangka memeriksa gambaran Tuhan ini kita tidak perlu meninggalkan warisan-warisan teologis yang telah kita terima dari pendahulu-pendahulu kita. Isi kelima isyu dalam konteks tadi membutuhkan Tuhan yang peduli di dalam kasihNya yang besar terhadap dunia ini. Maka teks Yohanes 3:16 menurut saya masih amat relevan. Oleh karena kasihNya yang habis-habisan terhadap dunia yang diciptakanNya, Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk melaksanakan karya penyelamatan. Karya penyelamatan ini tidak usah dimaknai secara abstrak atau sepotong-sepotong, melainkan menyeluruh, supaya manusia mengalami "hidup yang berkelimpahan" (Yoh 10:10). Dalam diskusi kita ada saran bahwa kita jangan terlalu mencolok menggambarkan Tuhan dalam wujud Trinitas atau Ketritunggalan, berhubung kita berada dalam konteks di mana Islam adalah mayoritas, dan seperti diketahui secara normatif Islam menolak paham Ketritunggalan ilahi. Namun menurut saya dialog dengan Islam tidak menuntut agar kita mengurangi pokok kepercayaan kita. Dialog berarti saya berusaha memahami yang lain, dan himbauan agar yang lain memahami saya. Bagaimana yang lain bisa memahami saya kalau apa yang menjadi pokok kepercayaan saya dihilangkan atau disembunyikan? Tentu saja kita perlu menghayati Ketritunggalan secara kontekstual, dan itu berarti menafsirkannya secara non-triumfalistik sebagai wujud solidaritas ilahi kepada manusia, seperti yang telah saya cobakan di atas.
b.Ecclesiology
Eklesiologi yang kita butuhkan di dalam menjawab kelima tuntutan konteks adalah eklesiologi yang di satu pihak tetap memperlihatkan identitas kita sebagai umat yang telah dipanggil Tuhan untuk melayani dunia ini, tetapi sekaligus juga sebuah identitas yang terbuka. Yang saya bayangkan adalah perumpamaan tentang perjamuan besar yang diadakan oleh Sang Tuan, yang ingin agar perjamuanNya dihadiri oleh segala macam golongan orang seperti yang diceritakan oleh Yesus di kisah-kisah Injil. Perjamuan makan di manapun juga merupakan simbol adanya status-quo di dalam masyarakat. Kita tidak mengundang sembarang orang untuk makan bersama kita. Tetapi Yesus justru memikirkan hal yang sebaliknya, dalam perjamuan makan yang Ia adakan, segala macam orang justru diundang, juga yang biasanya lewat dari perhatian kita. Di dalam persekutuan yang inklusif ini, perhatian pada kekudusan ("politics of holiness") berjalan bersama-sama dengan bela rasa ("politics of compassion"). Kekudusan seharusnya tidak membuat persekutuan Kristen memencilkan diri dari dunia, tetapi justru memberanikannya masuk ke dalam dunia untuk mengubahnya sehingga menjadi layak untuk kerajaan Allah.
Eklesiologi yang kita butuhkan di dalam menjawab kelima tuntutan konteks adalah eklesiologi yang di satu pihak tetap memperlihatkan identitas kita sebagai umat yang telah dipanggil Tuhan untuk melayani dunia ini, tetapi sekaligus juga sebuah identitas yang terbuka. Yang saya bayangkan adalah perumpamaan tentang perjamuan besar yang diadakan oleh Sang Tuan, yang ingin agar perjamuanNya dihadiri oleh segala macam golongan orang seperti yang diceritakan oleh Yesus di kisah-kisah Injil. Perjamuan makan di manapun juga merupakan simbol adanya status-quo di dalam masyarakat. Kita tidak mengundang sembarang orang untuk makan bersama kita. Tetapi Yesus justru memikirkan hal yang sebaliknya, dalam perjamuan makan yang Ia adakan, segala macam orang justru diundang, juga yang biasanya lewat dari perhatian kita. Di dalam persekutuan yang inklusif ini, perhatian pada kekudusan ("politics of holiness") berjalan bersama-sama dengan bela rasa ("politics of compassion"). Kekudusan seharusnya tidak membuat persekutuan Kristen memencilkan diri dari dunia, tetapi justru memberanikannya masuk ke dalam dunia untuk mengubahnya sehingga menjadi layak untuk kerajaan Allah.
Ketika John Wesley dan kawan-kawannya memperjuangkan kekudusan di wilayah Inggris, hal itu menyebabkan perubahan bukan saja di dalam batin orang, tetapi juga transformasi masyarakat berkat dihapuskannya undang-undang yang diskriminatif dan tidak manusiawi, dan digantikan dengan undang-undang yang lebih sesuai dengan persyaratan kehidupan masyarakat. Tekanan Calvinisme pada kedaulatan Allah (God’s sovereignty) di atas semua, justru membuat kita dapat memahami secara proporsional urutan kepentingan pokok-pokok yang biasanya dirujuk dalam masyarakat. Negara/Pemerintah, Pasar, Komunitas, bahkan Gereja dan Persekutuan semuanya penting, tetapi jika diperhadapkan pada kedaulatan Allah, maka semuanya menjadi nomor dua. Tetapi justru karena itu kita dapat menghargai semua pokok-pokok di atas pada tempatnya.
c.Missiology
Eklesiologi yang terbuka menghasilkan misi yang terbuka pula. Cita-cita misi adalah agar apa yang terkandung dalam simbol perjamuan besar di atas, dapat diperjuangkan secara konkret di dunia ini. Kita tetap berjuang untuk menyelamatkan manusia, tetapi manusia ini bukan kita tumpukkan di dalam gereja, melainkan kita pandang sebagai warga kerajaan Allah, yang lebih luas daripada gereja. Keterbukaan ini menuntut kita agar sikap gereja pejabat dan birokratisme yang sudah disinggung di atas, disingkirkan dari kehidupan bergereja kita. Misi tidak dapat berjalan kalau dihalangi oleh birokratisme. Itu tidak berarti kita menjadi anti birokrat. Organisasi tidak jalan kalau tidak ada birokrasi, misi juga tidak bisa jalan kalau tidak ada birokrasi. Namun di pihak lain misi tidak jalan kalau tidak ada presbiter yang bersemangat pelayanan, dan yang tidak melihat kedudukannya sebagai pejabat yang harus dilayani daripada melayani.
Eklesiologi yang terbuka menghasilkan misi yang terbuka pula. Cita-cita misi adalah agar apa yang terkandung dalam simbol perjamuan besar di atas, dapat diperjuangkan secara konkret di dunia ini. Kita tetap berjuang untuk menyelamatkan manusia, tetapi manusia ini bukan kita tumpukkan di dalam gereja, melainkan kita pandang sebagai warga kerajaan Allah, yang lebih luas daripada gereja. Keterbukaan ini menuntut kita agar sikap gereja pejabat dan birokratisme yang sudah disinggung di atas, disingkirkan dari kehidupan bergereja kita. Misi tidak dapat berjalan kalau dihalangi oleh birokratisme. Itu tidak berarti kita menjadi anti birokrat. Organisasi tidak jalan kalau tidak ada birokrasi, misi juga tidak bisa jalan kalau tidak ada birokrasi. Namun di pihak lain misi tidak jalan kalau tidak ada presbiter yang bersemangat pelayanan, dan yang tidak melihat kedudukannya sebagai pejabat yang harus dilayani daripada melayani.
Eklesiologi yang merupakan unsur dari teologi publik ini mengharuskan kita bermisi dengan menghadapkan wajah kita kepada publik. Itu berarti sarana-sarana berjemaat kita misalnya gedung-gedung peribadatan seharusnya menjadi pusat kehidupan masyarakat (community centers). Memang hal tsb tidak mudah dilakukan oleh karena kebanyakan arsitektur gedung-gedung gereja kita justru mengarahkan jemaat ke dalam, ke dirinya sendiri. Tuhan ada di dalam gedung gereja, bukan di luar gedung gereja. Teologi publik melihat Tuhan sebagai berada baik di dalam gereja maupun di luar, di dunia ini. Maka kita beribadah supaya dengan demikian mendapat kekuatan berjuang bersama Tuhan di luar gereja. Saya sudah pernah mengusulkan agar gedung dan kompleks gereja dibangun dengan memperhatikan bayangan tentang community centers ini. Kongkretnya bagaimana membangun gereja yang mempunyai dapur umum, mempunyai shelter dan mempunyai ruangan di mana siapa saja dapat datang dan berkomunikasi atau bersantai, sebelum meneruskan perjalanannya ke tempat lain. Sebenarnya GPIB sudah mempunyai modal besar yaitu konsep jemaat-jemaat Pelkes, namun kesan saya sekarang konsep ini sudah menjadi statis dan bahkan menjadi beban bagi GPIB. Saya mengusulkan agar konsep Pelkes ini didinamisir lagi, menjadi pelayanan yang tidak ditujukan tidak semata-mata untuk kepentingan jemaat (paroki) lagi, melainkan juga, dan terutama, untuk kepentingan masyarakat, terutama mereka yang berada di pinggiran. Dari pengalaman ambil bagian dalam transformasi masyarakat, gereja dapat memberikan suara atau pandangannya dalam situasi tertentu (tanpa menganggapnya sebagai fatwa), dalam rangka membangun publik opinion.
Penutup
Sebagai penutup perkenankanlah saya sharing mengenai pengalaman di Yogya: di satu pihak ada kesan baik terhadap pelayanan orang Kristiani terhadap korban-korban gempa (contoh Diakonia GKMI di Pundung, yang diikuti oleh gerakan Hisbullah). Tetapi di pihak lain ada juga kesan tidak baik terhadap orang Kristiani yang dicurigai mempunyai agenda terselubung dalam reaksi keras terhadap "Yogya Festival" (kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi oleh teman-teman kharismatik dengan menggunakan gedung olahraga Kridosono, tetapi di dalam selebarannya tidak disebutkan bahwa acara ini merupakan kebaktian). Kalau memberi kesan Kristenisasi, masyarakat menolak. Kalau kesaksian hidup yang nampak dalam kerja atau pelayanan sosial, masyarakat menerima. .
Sebagai penutup perkenankanlah saya sharing mengenai pengalaman di Yogya: di satu pihak ada kesan baik terhadap pelayanan orang Kristiani terhadap korban-korban gempa (contoh Diakonia GKMI di Pundung, yang diikuti oleh gerakan Hisbullah). Tetapi di pihak lain ada juga kesan tidak baik terhadap orang Kristiani yang dicurigai mempunyai agenda terselubung dalam reaksi keras terhadap "Yogya Festival" (kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi oleh teman-teman kharismatik dengan menggunakan gedung olahraga Kridosono, tetapi di dalam selebarannya tidak disebutkan bahwa acara ini merupakan kebaktian). Kalau memberi kesan Kristenisasi, masyarakat menolak. Kalau kesaksian hidup yang nampak dalam kerja atau pelayanan sosial, masyarakat menerima. .
Akhirnya, dari entusiasme masyarakat Indonesia terhadap PSSI saya mendapat kesan bahwa orang kembali suka kepada konsep "Indonesia". Tetapi karena ada prestasi, yaitu menang terhadap Bahrein, dan bermain bagus dalam melawan Arab Saudi meskipun kalah, dan akhirnya kalah dari Korea Selatan. Jadi kalau mau orang senang lagi pada Indonesia, harus ada prestasi di segala bidang, bukannya wanprestasi di segala bidang. Teologi publik sederhananya adalah kemampuan untuk menginspirasi masyarakat untuk keluar atau bangun dari keterpurukannya.
---------------------------
Wisma "Labuang Baji",
Yogyakarta, 15 Juli 2007.
Yogyakarta, 15 Juli 2007.
Catatan-catatan:
Singgih, Emanuel Gerrit, "Etnisitas, Kebangsaan, dan Gereja: Pergumulan Kristen di Indonesia pada Awal Abad ke-21", dalam Mengantisipasi Masa Depan, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004, pp. 124-157.
Wijaya, Yahya, " Perkembangan Teologi Politik di Indonesia: tanggapan atas Wahyu Satrio Wibowo", makalah seminar intern II dosen-dosen FTh UKDW, 23 September 2005.
Singgih, Emanuel Gerrit, "Etnisitas, Kebangsaan, dan Gereja: Pergumulan Kristen di Indonesia pada Awal Abad ke-21", dalam Mengantisipasi Masa Depan, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004, pp. 124-157.
Wijaya, Yahya, " Perkembangan Teologi Politik di Indonesia: tanggapan atas Wahyu Satrio Wibowo", makalah seminar intern II dosen-dosen FTh UKDW, 23 September 2005.
__________________________________________
disampaikan melalui milis GPIB :
Gerrit Singgih
Yth. pengurus milis GPIB,
Bersama ini saya mengirimkan tulisan yang berjudul "Membangun
teologi publik GPIB dalam rangka menjawab tantangan konteks Indonesia
masa kini" untuk dimuat dalam milis GPIB. Bahan ini saya berikan dalam
pertemuan sinodal GPIB mengenai Tatagereja GPIB di Yogyakarta 16-17 Juli
2007 dalam garis besarnya dan secara lisan, tetapi sekarang sudah saya
jadikan makalah lengkap dengan mempertimbangkan masukan-masukan pada
pertemuan tsb. Semoga berguna bagi wacana mengenai Tatagereja GPIB.
Teriiring salam dan doa,
Pdt. Prof. Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D.
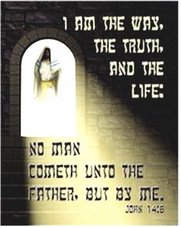


Tidak ada komentar:
Posting Komentar